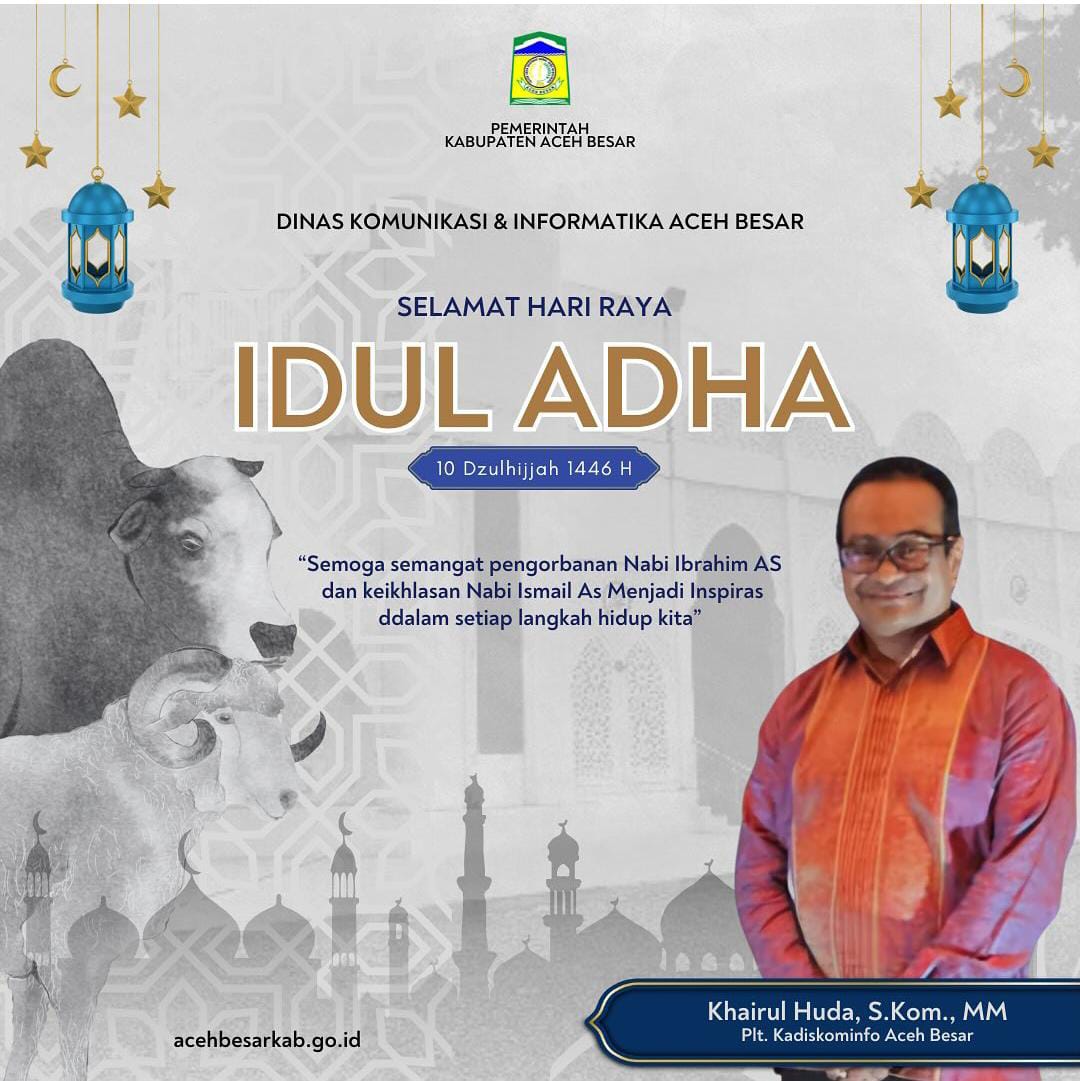Oleh : Sanusi ( Pemerhati Sosial Politik dari Kampung)
Di ruang operasi bernama republik, Aceh kembali terbentang di meja bedah. Lampu sorot berkilat bukan dari mahligai seremonial atau baliho selamat datang melainkan dari senter dokter forensik bernama KPK. Pada 21 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu mengirim “surat panggilan rontgen” bernomor B/5380/KSP.00/70-72/08/2025 kepada 24 kepala daerah di Aceh. Isinya sederhana tapi menusuk meminta serahkan data 10 proyek strategis, pokok pikiran (pokir) DPRD, hibah, dan bansos. Tenggat? Paling lambat 3 September 2025, seperti azan yang tak bisa ditawar, datang lima kali sehari.
Kita tahu, pokir adalah anak sah dari sistem perencanaan, selama tumbuh dalam pagar regulasi. Tapi sejarah daerah kita sering mengajarkan hal lain bahwa pokir bisa menjelma dompet lipat, hibah berubah menjadi kado keluarga, dan bansos yang mestinya pelampung justru dipakai jadi pelampiasan. KPK sendiri berulang kali mengingatkan, pokir bukan alat transaksi, catatan resmi mereka menandai area ini sebagai “garis merah” rawan suap, markup, dan penunjukan langsung.
Surat KPK kali ini terasa seperti membuka kembali laci-laci yang lama kita pura-pura lupa. Di laci pertama ada inidikasi korupsi Multiyears Contract (MYC) yang belakangan kembali hangat karena pembayarannya untuk tujuh paket penyesuaian harga disebut-sebut tak tercantum dalam APBA-P. Para penggiat antikorupsi menanyai logika akuntansi sekaligus keberanian politik yang menandatangani. Bila pembayaran menyelinap di luar dapur anggaran, siapa yang berkeringat di meja persidangan kelak?
Di laci kedua ada Kapal Aceh Hebat sebuah nama yang gagah, nasib yang megap-megap. Publik sudah mencium amis sejak masa perencanaan. KPK sempat memeriksa belasan pihak, harapan warga sederhana saja agar jangan biarkan kapal kasus ini karam di dermaga sunyi. Namun sampai hari ini, riak kabarnya lebih sering lahir dari rilis LSM ketimbang konferensi pers penegak hukum.
Laci ketiga bertuliskan Apendiks, sebuah kode nyeleneh di dokumen anggaran yang bahkan pejabat perencanaan mengaku “tak paham” asal-usulnya. Panitia khusus dewan pernah menyebut ada “10 orang” di balik skandal dana apendiks namun hingga kini belum juga diketahui nasibnya oleh publik. Apendiks ini ibarat catatan kaki yang ingin jadi bab utama namun tak ada dalam kamus nomenklatur, tapi tiba-tiba minta halaman sendiri
Maka ketika surat KPK menuntut daftar pokir, hibah, bansos, dan proyek strategis, itu sejatinya bukan sekadar permintaan data. Itu adalah audit atas ingatan, sebuah teguran halus bahwa pengalaman pahit di Aceh jangan diulang. Kita pernah menyaksikan dua gubernur yaitu Abdullah Puteh dan Irwandi Yusuf yang mengenakan rompi oranye yang lebih cocok disebut jubah tobat. Puteh diseret KPK pada 2004 dalam perkara helikopter Mi-2 dan akhirnya divonis 10 tahun, menjalani sekitar lima. Irwandi ditetapkan tersangka setelah OTT 2018, divonis 7 tahun karena suap DOKA dan gratifikasi, dengan eksekusi ke Sukamiskin setelah putusan inkrah. Sejarah itu bukan dongeng namun tercatat rapi di arsip resmi dan berita arus utama.
Apakah kita sedang menuju jilid ketiga? Belum tentu. Tapi gejalanya selalu berulang dimana proyek multiyears yang remang, kapal yang tak berlayar lurus, dan apendiks yang ingin jadi kitab. Di sisi lain, pokir yang seharusnya kanal aspirasi kerap menjadi bendungan kepentingan dimana bansos yang mesti menyasar rentan, justru menyasar perayaan. Karena itu, langkah KPK merapikan data sebelum musim politik lokal memuncak terasa seperti memasang stetoskop di dada Serambi Mekkah untuk mendengar detak jantung anggaran sebelum ia berdebar ke arah yang salah.
Literatur tata kelola mengajarkan, korupsi di daerah jarang lahir dari satu aktor. Ia tumbuh dari koalisi transaksional yang sebagian di eksekutif, sebagian di legislatif, sisanya di sekitar vendor yang pandai menari di antara celah aturan. Pokir menjadi “bahasa cinta” antar pihak, bansos menjadi “mahar legitimasi”, proyek strategis menjelma “cincin tunangan” untuk pesta pilkada dengan drama demokrasi. Teori principal menyebutkan agent menyebutnya moral hazard dimana KPK menyebutnya area rawan, namun rakyat menyebutnya capek.
Apa yang perlu dilakukan, selain menunggu stetoskop berbunyi lebih keras? Pertama, publikasi proaktif dimana semua data pokir, hibah, bansos, dan 10 proyek strategis yang diminta KPK harus dipajang lengkap dengan nomor kegiatan, nilai, pelaksana, dan progres di kanal resmi pemerintah daerah. Transparansi adalah vaksin yang tak menyembuhkan masa lalu, tapi mencegah mutasi berikutnya. Kedua, disiplin SIPD sehingga tak boleh ada transaksi “di luar kitab” dimana setiap penyesuaian MYC harus tertera dan bisa ditelusuri pada APBA/APBA-P. Ketiga, penguatan fungsi audit internal dan pelibatan masyarakat sipil untuk audit sosial, agar “apendiks” tak lagi menyelinap sebagai makhluk gaib. Catatan KPK juga menceritakan tentang ketidaksesuaian data pokir di daerah lain menunjukkan betapa rawannya hal sesederhana beda angka Rp 15 miliar vs Rp 17 miliar.
Akhirnya, seruan moral berkumandang, jangan biarkan Serambi Mekkah menjadi serambi maaf-maafan tiap lima tahun. Pemerintahan yang baik bukan pantomim meminta maaf, melainkan kebiasaan untuk tak berbuat salah. Surat KPK kali ini adalah cermin besar bahwa kalau wajah kita tampak kusam, jangan pecahkan cerminnya, cucilah muka anggarannya. Sebab kita semua sudah melihat betapa berat kain oranye itu di pundak seorang gubernur. Cukup dua nama untuk jadi pelajaran sejarah, semoga tak ada babak ketiga di Bumi Aceh tercinta.