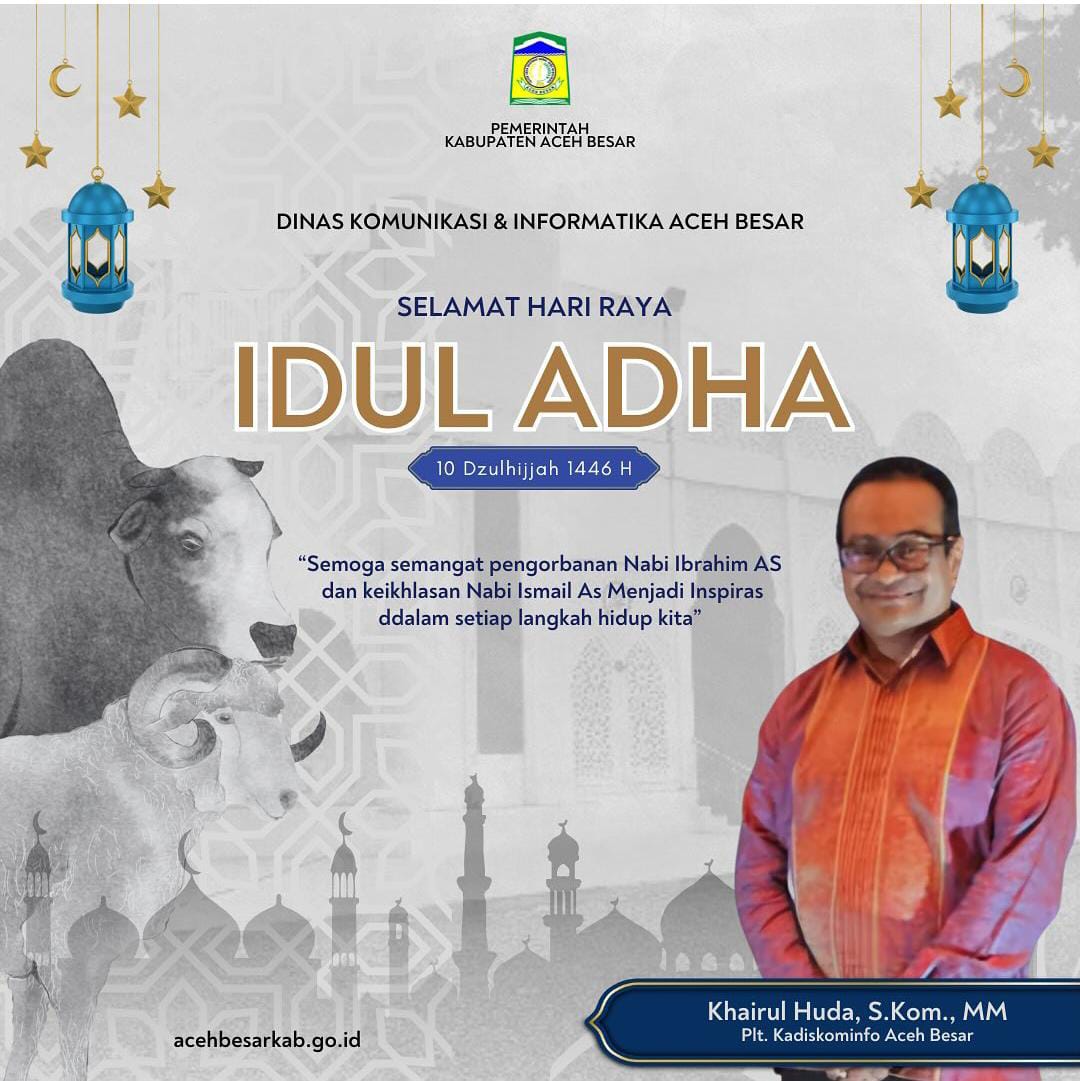Penulis : Sanusi (Aneuk Gampong dari Barat Selatan Aceh)
ACEH pernah dipandang dunia sebagai sebuah tanah yang suci, tempat di mana sejarah perjuangan dan spiritualitas berpadu dalam satu tubuh. Namun kini, di tengah harapan rakyat yang mendambakan kesejahteraan dari berkah kekhususan, sajadah yang dulu dipakai berdoa agar tanah ini bebas dari penindasan seakan ternodai oleh noda kapitalisme yang disapukan dengan karpet merah untuk investor. Panglima, yang dulu identik dengan simbol perlawanan, kini diuji apakah ia mampu menegakkan amanat sejarah atau justru terjebak dalam pusaran kepentingan korporasi.
Sejarah Aceh tidak bisa dilepaskan dari perebutan sumber daya alam. Dari masa kolonial Belanda hingga perang panjang yang berujung pada MoU Helsinki 2005, pertarungan inti selalu sama yaitu siapa yang menguasai emas, minyak, gas, hutan, dan perkebunan, dialah yang berkuasa atas Aceh. MoU Helsinki memberikan ruang istimewa berupa kekhususan dalam pengelolaan SDA. Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) adalah “sajadah politik” yang diwariskan bagi generasi kini, agar Aceh dapat bersujud pada kedaulatannya sendiri, bukan pada kemauan modal asing. Tetapi, sebagaimana diingatkan filsuf Karl Polanyi dalam The Great Transformation (1944), ketika tanah dan sumber daya hanya diperlakukan sebagai komoditas belaka tanpa ikatan sosial dan moral, maka yang lahir bukanlah kemakmuran, melainkan derita.
Fakta di lapangan memperlihatkan kecemasan itu. Laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dan data WALHI Aceh mencatat, hingga 2023 terdapat lebih dari 138 izin usaha pertambangan (IUP) di Aceh, dengan dominasi pada wilayah Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan. Di sektor perkebunan, menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), lebih dari 700 ribu hektar lahan di Aceh telah disulap menjadi perkebunan sawit, sebagian besar dikuasai korporasi besar. Namun ironisnya, kemiskinan di desa-desa sekitar tambang dan perkebunan masih bertahan di angka dua digit. Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh mencatat angka kemiskinan provinsi ini pada Maret 2024 mencapai 14,45%, jauh di atas rata-rata nasional 9,36%. Inilah paradoks dimana tanah kaya raya, rakyat tetap miskin.
Celakanya, fakta di lapangan akhir-akhir ini semakin sering terdengar dimana banyak investor datang ke kabupaten/kota dengan membawa nama “restu” dari Gubernur atau elite Aceh. Mereka menagih rekomendasi daerah, mengaku sudah mendapat persetujuan “atas”. Lalu, ketika konflik lahan atau pencemaran muncul, siapa yang menanggung akibatnya? Rakyat di kampung, bukan para pejabat yang menandatangani izin. Ini menjadikan pemerintah daerah seperti “penonton yang dipaksa membayar tiket,” terjebak dalam drama investasi tanpa perlindungan regulasi.
Padahal, kekhususan Aceh memberikan ruang untuk menunda, bahkan menghentikan sementara, semua pemberian izin eksplorasi dan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Aceh berhak menyusun regulasi sendiri berupa qanun atau peraturan gubernur yang lebih adil. Tapi hingga kini, qanun yang berpihak pada rakyat belum benar-benar hadir. Qanun Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, misalnya, lebih banyak mengatur soal teknis birokrasi ketimbang menghadirkan konsep “plasma pertambangan” yang sejajar dengan plasma perkebunan. Padahal konsep ini penting agar perusahaan wajib bermitra dengan masyarakat di daerah tambang, sehingga rakyat tak hanya jadi penonton di tanah leluhurnya.
Dalam literatur pembangunan, Amartya Sen dalam Development as Freedom (1999) menegaskan bahwa pembangunan sejati adalah pelebaran kebebasan manusia adalah kebebasan untuk hidup layak, untuk berpartisipasi, dan untuk menikmati hasil dari tanahnya sendiri. Jika pengelolaan SDA hanya memberi keuntungan pada korporasi dan elite, maka pembangunan itu gagal sejak awal. Aceh yang baru keluar dari konflik mestinya menjadikan keadilan distribusi SDA sebagai fondasi perdamaian. Jika tidak, maka seperti diingatkan Johan Galtung, perdamaian Aceh hanya akan menjadi negative peace atau sekadar ketiadaan perang bersenjata, tetapi konflik struktural tetap subur.
Lihatlah Barsela, wilayah barat-selatan Aceh yang dulu dijuluki “Aceh Masa Depan” oleh mantan Gubernur Ibrahim Hasan. Subur tanahnya, kaya mineralnya, hijau hutannya. Namun tanpa regulasi yang tegas, surga itu bisa berubah menjadi ladang sengketa. Janji pengukuran ulang HGU yang pernah digaungkan belum juga tuntas, sehingga tanah rakyat rawan diserap ke dalam peta perusahaan. Sengketa agraria pun menumpuk. Menurut catatan KPA, konflik agraria di Aceh terus meningkat, dengan kasus menonjol di Nagan Raya dan Aceh Barat terkait sawit. Jika situasi ini berlanjut, rakyat Barsela akan menjadi “tamu di rumahnya sendiri”, penonton lapar di lumbung padi.
Di sinilah ujian sesungguhnya bagi Mualem. Apakah ia akan memanfaatkan ruang kekhususan Aceh untuk mempercepat lahirnya qanun pertambangan rakyat, menata ulang HGU, dan memastikan rakyat ikut serta dalam setiap investasi? Atau justru mengikuti jejak pemimpin sebelumnya, yang lebih sibuk menghamparkan karpet merah bagi investor? Seorang panglima pernah menjadi simbol keberanian rakyat, tetapi seorang panglima yang alpa bisa menjelma sekadar penjaga pintu modal.
Sajadah di sini bukanlah hiasan, namun sajadah adalah simbol kesucian, warisan spiritual, sekaligus ruang penghubung dengan Tuhan. Jika sajadah itu ternodai oleh noda kerakusan dan ketidakadilan, maka generasi mendatang hanya akan mengenangnya sebagai benda tua yang tersimpan di lemari, tanpa makna. Begitu pula UUPA, MoU Helsinki, dan kekhususan Aceh yang bisa jadi warisan suci, atau sekadar catatan usang di lembaran sejarah.
Aceh berdiri di persimpangan, antara menjadikan kekhususan sebagai jalan pembebasan, atau membiarkannya ternodai sebagai komoditas politik. Dan di tengah persimpangan ini, panglima diuji. Rakyat menunggu, apakah ia masih sujud di atas sajadah yang suci, ataukah sudah nyaman di atas karpet merah yang digelar investor.